Perjalanan Menyusui Penyintas TBC
Setahun yang lalu di pertengahan bulan Juni, saya dinyatakan positif TBC dengan satu kerusakan paru. Kalo kata dokter Lusi (dokter paru teruwu se-Depok), paru-paru saya sudah borok. Sudah berlubang disana-sini macam luka ghosting, sehingga tidak bisa difungsikan lagi.
Setahun yang lalu di tanggal yang sama ketika cerita ini ditulis, saya terluka. Terluka karena sakit dan merasa gagal memberikan ASI untuk anak kedua. Betapapun saya berusaha, nyatanya cuma tetesan air susu yang keluar. Itu pun, rasanya saya seperti tidak punya payudara. (Agak dramatis, tapi emang gitu deh! JJ)
Saya itu tipe perempuan yang mungil. Hihihi. Waktu hamil kayaknya paling mentok ada di angka 52 atau 53 gitu. Pasca melahirkan 45 udah gembil lumayan. Nah, waktu terserang TBC itu, timbangan merosot 10 kg. Yupiii, 35 kg. Tidak kurang tidak lebih. Dibuat jalan, limbung terus. Massa tubuh nggak sesuai kebutuhan.
Automatically, semua bagian tubuh menyusut. Termasuk payudara yang menjadi aset menyusui. Kalo diingat-ingat lagi, saya baru nggeh kenapa si bayik yang waktu itu masih 6,5 bulan menangis tiap selesai nenen. Ya, apalagi kalo bukan karena kelaparan. Makan masih di tahap belajar, eh…stok makanan di tubuh emaknya antara ada dan tiada.
Yang saya ingat di waktu masih mampu bepergian untuk belanja. Saya tiba-tiba kepikiran membeli botol susu lengkap dengan susu formula serta pembersihnya. Feeling aja kayaknya bakal butuh. Dan ternyata memang butuh! Saya demam tinggi berulang setelah 3 hari mengonsumsi obat dokter. Bisa dibayangkan, udah kurus, demam pulak! Boro-boro nyusuin, bangun aja butuh perjuangan. Jadi, si bayik minum sufor sejak hari itu.
Sedih dalam taraf “Ya, Allah kenapa mesti gue sih?”. Udah terpuruk syekali.
Berhubung Covid-19 waktu itu sedang merajalela (sekarang malah tambah menjadi), saya ketar-ketir jugak. Jangan-jangan batuk-batuk selama ini, demam yang tak kunjung berhenti adalah Coroncee! Duh, gimana anak-anak, orang yang bantu-bantu di rumah? Udah hopeless yang nggak bisa diceritain lagi pokoknya.
Setelah Rapid Test dan diperiksa pake cek darah, tes Mantoux, CT Scan terdeteksilah bahwa saya TB Paru. Bisa cukup bernapas legalah saat itu.
Waktu opname, entah kenapa saya ingat pumping. Sempat khawatir kalo payudara bakal bengkak. Terus dibela-belain marmet. Hahaha. Masih nggak sadar diri kalo badan aja nggak kuat berdiri. Marmet sebentar aja, tangan udah kebas. Akhirnya, pasrah juga. “Gue emang lagi nggak menghasilkan ASI!”
Waktu pertama kali mengonsumsi obat TB, syok berat. Karena jumlahnya banyaaak banget! Salah satu faktornya karena saya opname di rumah sakit swasta. Mereka tidak punya obat ala WHO untuk TBC. Eh, info aja sih ini. Jadi, kata dokter kedua pasca pemulihan kalo obat yang saya konsumsi dari rumah sakit swasta memang lebih banyak. Soalnya mereka nggak dapet akses mendapatkan obat OAT. Tapi, tetep sama aja. Beda di dosisnya aja. Kalo di RSUD atau PUSKESMAS, 3 butir cukup. Nah, kalo di swasta 7 butir atau lebih kayaknya.
Kembali ke perASIan yak. Setelah konsultasi dengan dokter Lusi, saya tetap diperbolehkan untuk menyusui. Obat yang saya minum masih aman untuk si bayik. Kalo pun ada yang berpengaruh ke ASI itu sedikit sajo. Alhamdulillaaah!
Nah, setelah selesai rawat inap saya masih belum bisa menyusui. Si bayik masih minum sufor. Saya sudah ikhlas. Emang nggak bisa dipaksain.
Seminggu kemudian, ketika melakukan perjalanan udara. Antara deg-degan dan khawatir, akhirnya si bayik menyusu kembali. Ini pertama kalinya setelah 2 minggu lebih tidak ada yang ndhusel-ndhusel minta nenen.
Ini relaktasi yang tidak disengaja. Karena ini perjalanan pertama si bayik, apalagi naik pesawat tentu terasa berbeda. Tekanan udara pasti akan mengganggunya. Saya sudah menyediakan airmurf, tapi tidak mau dipakai. Di pesawat mulai rewel karena ngantuk. Dan, menyusui sepertinya cara terakhir yang bisa saya lakukan supaya dia tenang. Bersyukur, proses menyusui kembali berjalan dengan gembira.
Selanjutnya, saya kombinasikan antara sufor dan ASI. Dengan cacatan selama pasca pemulihan itu, saya selalu menggunakan masker selama 2 bulan ketika di dalam atau keluar rumah. Nggak ada cium-cium atau tempel-tempel muka untuk menghindari penularan kuman. Setelah cukup kuat, saya lepas sufor dan full ASI
Hari ini, si bayik sudah berusia 19 bulan dan sebentar lagi mau sapih. Sudah sounding-sounding sejak sekarang. Sungguh tak terasa.
Pengalaman ini sungguh menampar saya (yang idealis tentang pengasuhan anak). Bahwa mau ASI atau Sufor itu sama-sama baik. Semua pilihan-pilihan untuk anak dan keluarga, tergantung kondisi dan pilihan tiap individu. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang sungguh di luar kendali kita. Seperti saya, siapa yang tahu akan sakit. Siapa yang mau jugak?


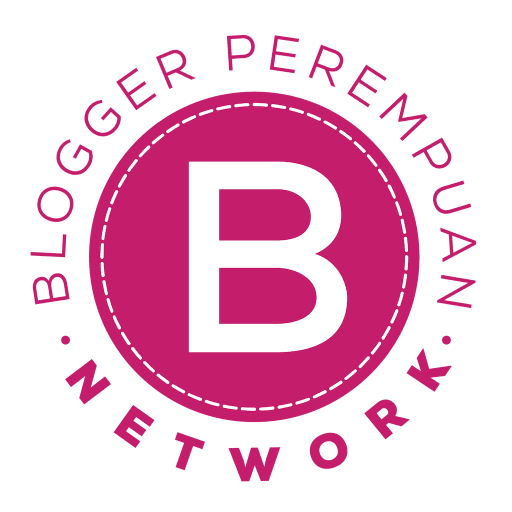

Heuu aku inget ini buukk
Rasanya waktu itu (kalo aku mampu) pengen aku boyong anak anak mu ke rumah..
Tapi aku salut km though, seterooong women i have everr meettt !.
Salam buat teteh dan adek ya !
Salam buat Mika Ubay Maryam jugak yaaa… 😍😍😍